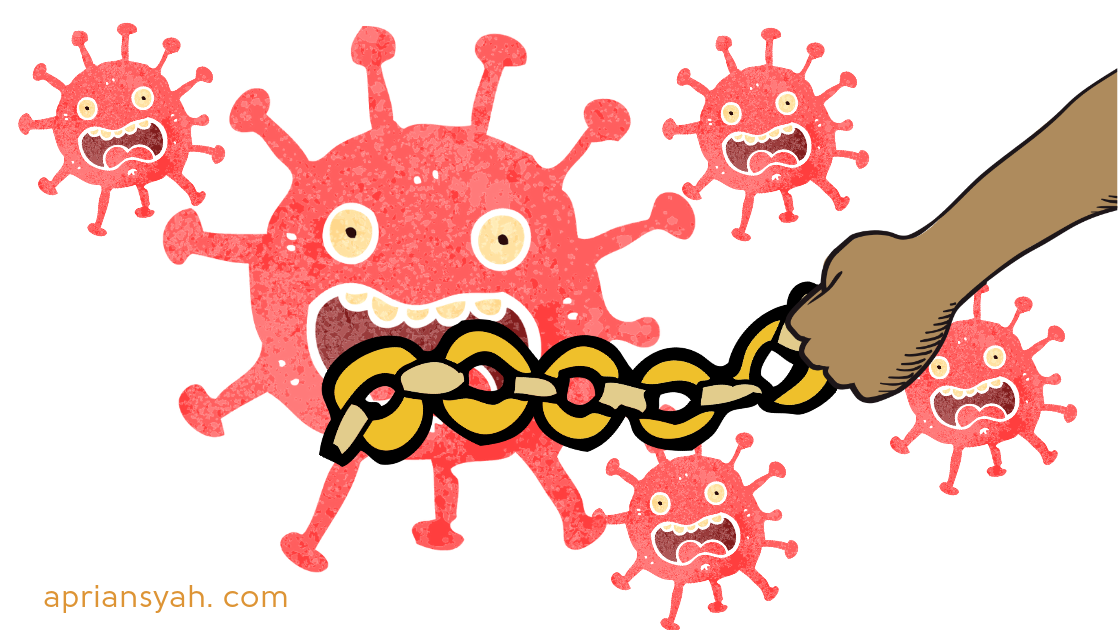Senin tanggal 12 Februari 2018, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU MD3 pada rapat paripurna kemarin. Pada rapat paripurna tersebut diwarnai aksi walkout dari fraksi partai NasDem dan dari fraksi partai PPP yang tidak setuju akan revisi. Banyak kalangan terutama dari pengamat yang menyayangkan dan cenderung tidak setuju akan revisi tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan direvisinya UU MD3 menunjukkan bahwa DPR hanya sibuk kompromi bagi-bagi kursi dan melindungi diri.
Bagi beberapa kalangan, revisi tersebut hanya menegaskan bahwa DPR ingin semakin berkuasa, ingin kebal hukum, dan antikritik. Pasal-pasal yang direvisi pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang dinilai syarat kompromi politik ialah tambahan pasl 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa oleh polisi. Kedua adalah pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap siapa pun yang menghina/merendahkan DPR dan anggota DPR. Ketiga adalah pasal 245 menganai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan terhadap anggota DPR harus melalui izin tertulis presiden dan atas pertimbangan MKD. Selain itu yang menjadi sorotan adalah penambahan jatan kursi pimpinan di DPR dan MPR yang menegaskan bahwa revisi syarat bagi-bagi kursi.
Pada tambahan pasal 73, DPR bisa menggunakan pihak kepolisian untuk pemanggilan paksa kepada siapa pun yang dianggap mangkir dari pemanggilan DPR. Disini DPR ibarat punya kuasa seperti lembaga hukum yang bisa memanggil paksa seseorang dan “menyeretnya” untuk dimintai keterangan. Padahal DPR hanya punya hak untuk meminta keterangan BUKAN berkewajiban saya pikir. Kedua adalah pasal 122 terkait langkah hukum MKD kepada siapa pun yang dianggap merendahkan DPR dan anggota DPR. Menurut penulis hal tersebut bukanlah kewenangan dari MKD. MKD adalah lembaga internal yang berfungsi sebagai fungsi kontrol terhadap anggotanya yang berarti kewenangan itu berfungsi ke dalam bukan ke luar. Sedangkan pada pasal 245 mengenai proses hukum terhadap anggota dewan harus melalui izin tertulis presiden dan pertimbangan MKD seolah ingin menggambarkan bahwa DPR kebal hukum dan antikritik. Dengan disahkannya pasal 245 akan semakin mempersulit pihak kepolisan dan kejaksaan untuk memproses anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Sebelum disahkan saja sudah ada beberapa kasus mengenai dugaan pelanggaran anggot dewan yang hanya menguap di kepolisian maupun kejaksaan (lihat detiknews.com).
Yang terakhir yang menjadi sorotan ialah penambahan kursi pimpinan anggota DPR dan MPR. Sudah sangat jelas hal ini merupakan kompromi politik untuk kepentingan masing-masing parpol saja. Dengan bertambahnya kursi pimpinan, maka parpol tertentu akan mempunyai kewenangan lebih dan tentunya uang kas lebih untuk partainya. Beberapa parpol beranggapan bahwa kursi pimpinan dewan bermakna naiknya elektabilitas partai karena seringnya sorotan media terhadap pimpinan DPR maupun MPR, namun menurut saya itu tidaklah signifikan mengingat tetap saja tergantung dari citra yang dibentuk oleh orang tersebut. Penambahan kursi pimpinan bisa kita artikan juga pemborosan untuk ke-sekian kalinya yang dilakukan berjamaah oleh anggota dewan karena dengan bertambahya kursi pimpinan maka anggaran yang harus dikeluarkan akan bertambah pula dan saya yakin kenaikan anggaran tidak akan sejalan dengan membaiknya kinerja anggota dewan.
Pada akhirnya mungkin kita hanya akan mengelus dada melihat tingkah laku anggota dewan dan berharap biarlah Tuhan yang bekerja.
“Wakil rakyat seharusnya merakyat jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu ‘setuju'”.
Iwan Fals-Surat Buat Wakil Rakyat